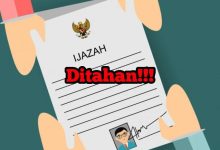Konflik Horizontal 1945-1949 Dipicu Kecemburuan dan Kecurigaan Sosial

Senin, 17 April 2017
Indonesiaplus.id – Konflik terbuka antara Indonesia – Belanda pada kurun 1945-1949 telah meninggalkan ‘luka sejarah’ bagi kedua bangsa. Terlebih bagi Indonesia telah mengoyak dan turut mendorong konflik horizontal.
“Konflik kedua negara, baik secara politik maupun militer berakhir dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 di Den Haag, ” ujar Direktur Sejarah, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Triana Wulandari, dalam Diskusi Terbatas Konflik Indonesia-Belanda (1945-1949) dalam Pandangan Generasi Terkini, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Sabtu (15/4/2017).
Namun, kata Triana, pasca masa revolusi nasional secara langsung mendorong ketegangan sosial yang sarat dengan kompetisi dan potensi konflik di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.
“Keberadaan, peran kelompok sosial dan interaksinya di masyarakat yang bersifat kompetitif turut menciptakan situasi konflik sosial besar, baik bersifat vertical maupun horizontal, ” katanya.
Dalam konflik vertical, kelompok ini berperan menghancurkan kekuatan elite politik lama yang berusaha mempertahankan dominasi status quo. Seperti peristiwa revolusi sosial di Aceh dan Sumatra Timur pada Maret 1946; gerakan anti-swapraja di Surakarta; serta peristiwa tiga daerah di pesisir utara Jawa dalam waktu bersamaan.
“Kondisi demikian sebagai bukti konflik vertical ada dan dikaitkan penggantian struktur lama ke struktur baru, yang dijadikan sebagai bagian dari konflik politik antara Indonesia – Belanda,” katanya.
Konflik horizontal di kalangan kelompok sosial marak terjadi selama masa revolusi itu. Namun, praktis sulit dihubungkan dengan konteks konflik nasional antara Indonesia – Belanda.
Sebagai pemicu jelas lebih pada kecemburuan atau kecurigaan sosial (social jealously and suspicious) suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai saingan untuk memainkan peran dominan kelak pasca revolusi.
“Konflik horizontal terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Pembunuhan terhadap kelompok berbeda status sosial, ekonomi, fisik serta ideologis, ” terangnya.
Juga, peristiwa Tangerang (1946), Bagan Siapi-Api (1948), pembantaian di Blabak dan Talun di Magelang pada 20 Desember 1948, serta peristiwa serupa yang bersifat genocide di Jawa Timur.
“Tidak ada kaitan dengan konflik elite nasional saat itu. Lebih disebabkan kecemburuan dan kecurigaan social yang mudah dikobarkan setelah diberi pembenaran dengan unsur ideologis tertentu, ” ungkapnya.
Konflik horizontal yang mendekati afiliasi konflik nasional, kekerasan mengatasnamakan agama. Seperti peristiwa di Bekasi (1946), pembunuhan rohaniawan di Muntilan di akhir Desember 1948, serta pembakaran rumah ibadah di Ambarawa pada saat bersamaan.
Ciri lain dari konflik horizontal adalah bersifat local. Meskipun tersebar dan dilakukan kolektif serta terencana. Berbeda dengan konflik sosial yang lebih bersifat structural dan bisa dianggap sebagai bagian atau terkait langsung dengan konflik nasional.
“Karena tidak menjadi bagian langsung, konflik horizontal hampir tidak pernah dimasukkan dalam historiografi Indonesia, ketika menguraikan peristiwa masa revolusi nasional, ” katanya.
Konflik seperti itu dengan segala ciri dan polanya sering terjadi dan terulang. Di era reformasi yang diisi kebebasan dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.[Ham]